Penerima Gratifikasi Bukan Cuma Jaksa, Tapi Kenapa Hukum Berbeda?”
- account_circle Redaksi
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 7

Tegarnews.co.id – Jakarta, 12 Oktober 2025- Dalam sistem hukum Indonesia, gratifikasi kerap dipahami sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling sulit dibedakan dari hadiah atau pemberian biasa. Namun yang menarik dicermati, terdapat perbedaan mencolok dalam perlakuan hukum terhadap pelaku gratifikasi — terutama jika dibandingkan antara jaksa dan pejabat publik lainnya.
Baru-baru ini, publik digemparkan oleh kasus dua eks Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp500 juta. Alih-alih dijatuhi hukuman pidana, keduanya hanya diberikan sanksi administratif berupa pemindahan ke bagian Tata Usaha. Nilai gratifikasi yang besar itu tentu memicu pertanyaan publik: mengapa pelanggaran seberat itu justru diselesaikan dengan sanksi ringan, di saat Kejaksaan sedang mendapat sorotan atas perannya menyelamatkan ratusan triliun uang negara?
Sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ancaman pidananya jelas: paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dengan denda hingga Rp1 miliar.
Namun dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap aparat penegak hukum — terutama jaksa — kerap menunjukkan kelonggaran. Sanksi yang diberikan sering kali hanya bersifat etik atau administratif, bukan pidana sebagaimana mestinya.
Perlakuan berbeda ini memperlihatkan adanya standar ganda (double standard). Ketika pelaku berasal dari kalangan jaksa, proses hukum cenderung berhenti di ranah internal. Sebaliknya, jika pelaku adalah ASN biasa, kepala dinas, atau kepala daerah, mereka kerap langsung dijadikan tersangka, bahkan divonis bertahun-tahun penjara.
Padahal, jaksa merupakan penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan integritas, bukan penerima gratifikasi. Dalam Kode Etik Jaksa serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 dan PERJA Nomor 4 Tahun 2024, sudah secara tegas dinyatakan larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.
Ironisnya, sanksi yang diterapkan kepada aparat penegak hukum justru lebih ringan dibandingkan sanksi bagi rakyat biasa. Inilah yang menimbulkan kesan bahwa hukum di negeri ini masih tunduk pada hierarki sosial: semakin tinggi jabatan, semakin ringan hukuman.
Keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Ketika publik melihat adanya ketimpangan sanksi antara penerima gratifikasi dari kalangan jaksa dan non-jaksa, kepercayaan terhadap sistem hukum otomatis terkikis.
Masyarakat akan kehilangan keyakinan bahwa hukum adalah alat moral negara. Jika aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi justru dilindungi oleh sistemnya sendiri, maka hukum hanya akan menjadi simbol tanpa makna.
Ke depan, Komisi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memastikan bahwa penanganan kasus gratifikasi terhadap aparat penegak hukum tidak boleh berhenti di level etik atau administratif semata.
Publik berhak menuntut agar setiap jaksa yang menerima gratifikasi diproses secara pidana, sebagaimana warga negara lainnya.
Hanya dengan langkah itu, hukum bisa kembali pada hakikatnya — bukan alat kekuasaan, melainkan alat keadilan.
- Penulis: Redaksi
- Editor: HUSEN
- Sumber: Junaedi Rusli

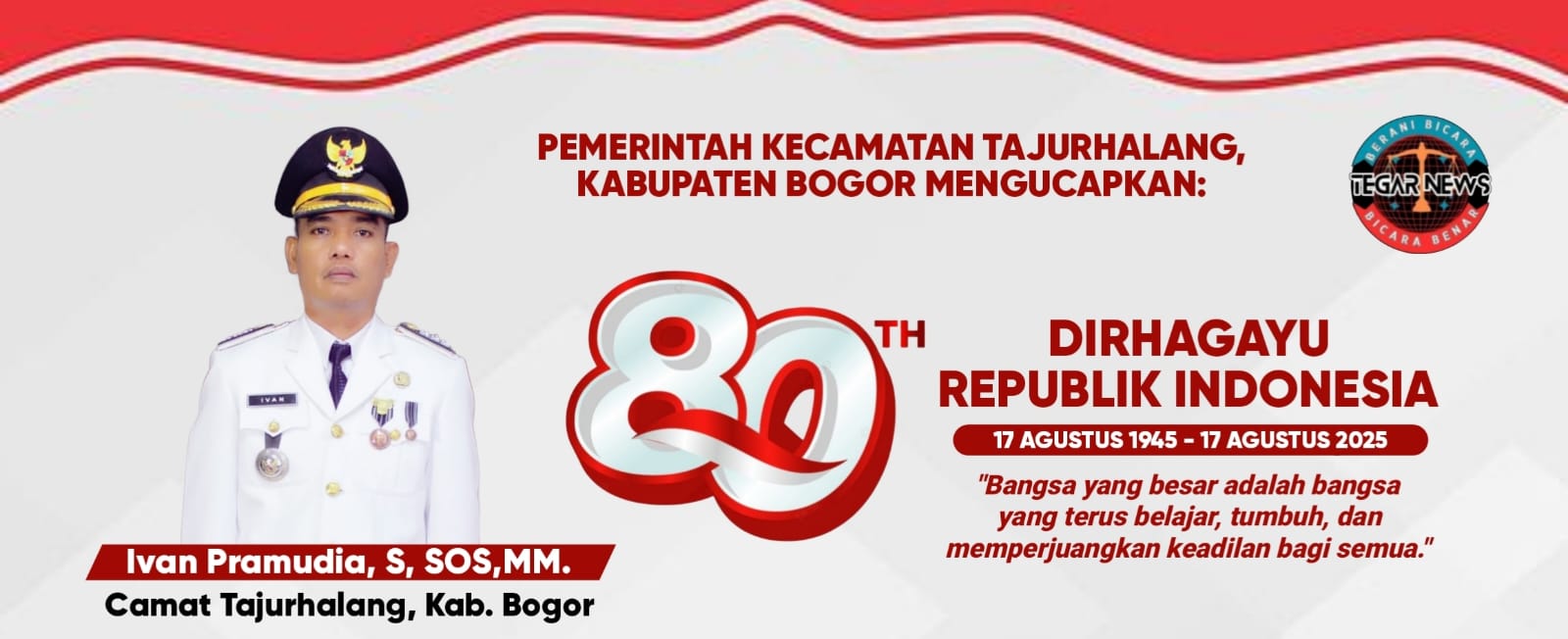





































Saat ini belum ada komentar